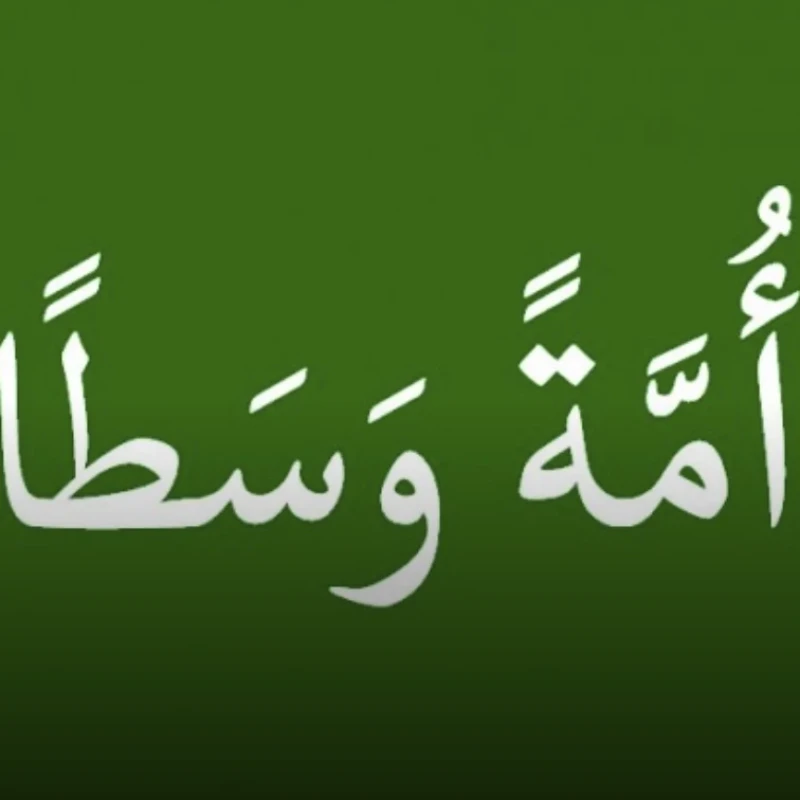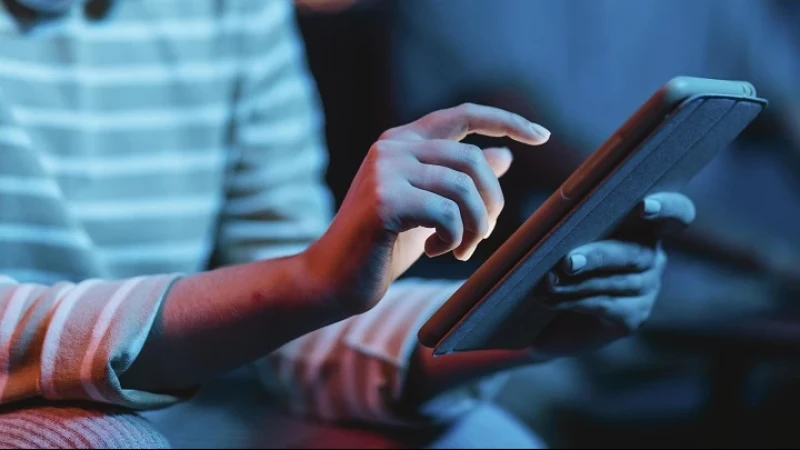Fatwa Kebisingan Dari Masjid Pekojan: Sayyid Utsman Dalam “Adab Al-Insan”
Selasa, 6 Juni 2023 | 07:00 WIB
Dalam catatan Berg (2010) setidaknya mulai abad ke-18, kehidupan keagamaan masyarakat muslim di Jakarta mulai diwarnai oleh kehadiran ulama dari komunitas Hadrami. Tokoh ulama populer pada periode tersebut adalah Sayyid Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus yang wafat pada tahun 1798 dan dimakamkan di Luar Batang.
Ulama selanjutnya yang dikenal luas di kalangan muslim Nusantara adalah Salim bin Abdullah bin Sumayr yang menulis kitab Safinatun Najah. Salim bin Sumayr wafat di Batavia pada 1854 dan dimakamkan di Tanah Abang. Pengaruh besarnya terlihat dari popularitas kitab fiqih karangannya yang hingga saat ini masih banyak dipelajari oleh santri di lingkungan pesantren.
Dari beberapa ulama Hadrami yang tinggal di Jakarta, satu nama yang perlu disebut adalah Sayyid Utsman bin Yahya. Cukup banyak peneliti yang menganggap bahwa Sayyid Utsman adalah ulama Hadrami paling dikenal luas di wilayah Nusantara pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Azra, 2002; Berg, 2010; dan Steenbrink, 1984). Hal ini dapat menggambarkan bagaimana pentingnya posisi tokoh kelahiran Pekojan ini dalam periode tersebut.
Salah satu aspek yang mungkin membuat Sayyid Utsman dikenal luas adalah produktivitasnya dalam menghasilkan karya tulis. Dalam perhitungan Berg (2010) ia telah menulis 38 judul buku. Steenbrink (1984) menunjukkan jumlah yang lebih banyak dengan menyatakan bahwa Sayyid Utsman telah menulis lebih dari 50 karangan. Bahkan dalam “Ini Daftar Nama Kitab-Kitab dan Jadwal-Jadwal yang Dikarang dan Dicetak oleh Sayyid Utsman," jumlah buku yang dikarangnya berjumlah sekitar seratus. Menariknya, sebagian besar karyanya ditulis dalam bahasa Melayu (Azra, 2002).
Kecenderungan Sayyid Utsman yang lebih memilih menulis dalam bahasa Melayu setidaknya menunjukkan suatu identitas kultural yang hibrida. Menurut Alatas (2010), identitas hibrida adalah sesuatu yang lazim melekat pada komunitas Hadrami di Nusantara. Pada satu sisi, kalangan Hadrami menjadi pribumi dan mengintegrasikan diri dengan situasi sosio-kultral lokal dan pada saat yang sama tidak melepaskan akar identitas lamanya dan tetap menjadi bagian dari jejaring diaspora Hadrami.
Sensibilitas kultural inilah nampaknya yang mendorong Sayyid Utsman untuk turut terlibat dalam wacana keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat lokal. Seperti ketika ia menulis kitab Tawdhih al-Adillati ‘ala Syuruthi Syuhudi Ahillati, tentang ilmu falaq dan penentuan bulan Ramadhan untuk merespon perdebatan di tengah masyarakat Jakarta yang pada 1882 memulai puasa Ramadhan pada hari yang berbeda (Steenbrink, 1984).
Tanggapan terhadap dinamika keagamaan masyarakat lokal juga terlihat dalam kitab Adab Al-Insan yang ditulis pada 1885. Dalam salah satu pasal di kitab tersebut, Sayyid Utsman mengingatkan bagaimana etika penggunaan beduk untuk keperluan ibadah. Menurut Sayyid Utsman beduk yang dalam tradisi muslim di Nusantara sering digunakan sebagai penanda waktu ibadah, tidak boleh dibunyikan sampai mengganggu orang lain yang butuh ketengangan semisal orang sakit atau dengan sengaja dimaksudkan untuk mengganggu tidur seseorang.
Argumen Sayyid Utsman ini menarik terutama jika hendak melihat konteks sosial masyarakat Jakarta yang plural, baik dalam aspek agama, kelas sosial, maupun tradisi. Mungkin saja, larangan untuk membuat kebisingan dengan beduk didorong oleh kesadaran Sayyid Utsman terhadap situasi sosiologis masyarakat Jakarta yang terdiri dari beragam identitas. Karena bisa jadi tidak semua orang dapat maklum dengan tabuhan beduk yang dipukul keras dan dalam waktu yang lama.
Berselang hampir satu abad kemudian, Gus Dur juga menulis sebuah artikel di majalah Tempo pada tahu 1982 berjudul “Islam Kaset” dan Kebisingannya. Dalam tulisannya, Gus Dur mengkritik praktik penggunaan pengeras suara yang dilakukan oleh masyarakat ketika hendak memberitahukan waktu ibadah.
Menurut Gus Dur, tidak elok jika seruan agama disampaikan dengan cara yang kurang baik, apalagi jika sampai mengganggu orang lain. Karena dalam lingkup masyarakat muslim saja, terdapat kelompok orang tertentu yang semestinya tidak diganggu waktu istirahatnya semisal orang jompo yang membutuhkan tidur cukup dan tidak bisa dikagetkan, perempuan haid, dan anak yang belum akil baligh.
Menarik untuk membaca secara komparatif tulisan Sayyid Utsman dengan artikel Gus Dur yang berjarak hampir satu abad ini. Kesamaan di antara keduanya adalah kepekaan terhadap situasi keagamaan masyarakat. Adapun sasaran kritik yang dituju oleh keduanya bisa merefleksikan sikap kultural masing-masing.
Sayyid Utsman nampak tengah menunjukkan mulusnya proses asimilasinya sebagai seseorang dari komunitas Hadrami dengan kebudayaan lokal. Kritiknya yang disampaikan dalam bahasa Melayu dan menggunakan beberapa istilah lokal juga semakin memperlihatkan sikap kulturalnya yang hibrida. Kutipan dari bagian kitab Adab Al-Insan ini mungkin bisa sedikit lebih jelas memperlihatkannya:
“… dan tiada ada beduk di negeri Arab maka yang dibuat kasih tahu orang-orang akan waktu sembahyang yaitu hanya adzan, adapun itu beduk di tanah Jawa dibuat membantu adzan kasih tahu orang-orang yang jauh supaya ia dapat tahu waktu sembahyang, atau buka puasa, atau makan sahur."
Kutipan di atas, setidaknya bisa menggambarkan pemahaman Sayyid Utsman terhadap praktik kebudayaan lokal. Selain itu, menarik untuk melihat bagaimana kata shalat justru digantikan oleh kata sembahyang. Bisa jadi hal ini dilakukan untuk semakin memudahkan penyampaian gagasannya kepada masyarakat. Karena menurut Steenbrink (1984), Sayyid Utsman memiliki kecenderungan untuk mengarang kitab-kitab pendek dalam format brosur yang bisa didapatkan dengan harga murah serta dengan menggunakan bahasa dipahami oleh kebanyakan masyarakat.
Masjid sebagai Pusat Aktivitas Keagamaan
Hari Jum’at 2 September 1898, masjid Pekojan mengirimkan do’a bagi Ratu Wilhemina yang diangkat sebagai pimpinan Kerajaan Belanda. Do’a tersebut diinisiasi oleh Sayyid Utsman, dan bahkan teksnya disebar ke banyak wilayah di Jawa dan Madura (Kaptein, 1998).
Terlepas dari berbagai kontroversinya, momen do’a untuk Ratu Wilhemina tersebut bisa dianggap sebagai tanda bahwa Masjid Pekojan adalah pusat aktivitas keagamaan Sayyid Utsman. Dari masjid itulah, pengajaran agama dilakukan dan fatwa-fatwa yang dibuat oleh Sayyid Utsman disebarkan.
Menurut Syarif dan Ansor (2020), dalam masyarakat Betawi, masjid bukan hanya menjadi pusat kegiatan peribadatan, melainkan juga memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan agama serta titik awal penyebararan wacana sosial-keagamaan ke tengah masyarakat (Syarif dan Ansor, 2020).
Maka bisa dipahami jika Masjid Pekojan ini memiliki makna tersendiri bagi karir Sayyid Utsman sebagi Mufti Betawi. Masyarakat lokal sendiri banyak yang antusias terhadap dakwah keagamaan yang dilakukan oleh Sayyid Utsman. Menurut Berg (2010), komunitas Hadrami dan masyarat lokal sama-sama mengakui kepakarannya dalam bidang agama.
Penerimaan masyarakat lokal ini terbilang lazim karena biasanya kalangan sayyid atau habaib memiliki posisi istimewa di tengah masyarakat muslim tradisional di Indonesia. Jika melihat secara khusus dalam kasus Jakarta, masyarakat muslim Betawi sering melihat habaib bukan hanya sebagai ulama, melainkan menganggap sebagian dari mereka sebagai wali (Rijal, 2022).
Meskipun demikian, nama Sayyid Utsman mungkin kurang populer disambut dalam konteks masyarakat pasca-kolonial. Sikap akomodatifnya terhadap Pemerintahan Kolonial Belanda adalah sebab dari kurangnya perhatian pada sosok ini.
Namun, terlepas dari berbagai tafsiran atas sikap politiknya di masa lalu, pribadi Sayyid Utsman tetap menjadi figur penting dalam perkembangan keagamaan masyarakat muslim di Jakarta. Karena jika hendak menimbang lebih tenang, Sayyid Utsman ternyata salah satu pendukung Sarekat Islam. Salah satu organisasi tempat bertumbuhnya nasionalisme Indonesia.
Sumber:
Alatas, Ismail Fajrie, “Menjadi Arab: Komunitas Hadrami, Ilmu Pengetahuan Kolonial, dan Etnisitas” pengantar dalam L. W. C. van den Berg, Orang Arab di Nusantara, Depok: Komunitas Bambu, 2010.
Azra, Azyumardi, Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal, Bandung: Mizan, 2002.
Berg, L. W. C. van den, Orang Arab di Nusantara, Depok: Komunitas Bambu, 2010.
Kaptein, Nico, “The Sayyid and the Queen: Sayyid Uthman on The Queen Wilhemina’s Inauguration on The Throne of The Netherlands in 1898”, Journal of Islamic Studies Vol. 9 No. 2 pp. 158-177.
Rijal, Syamsul, Habaib dan Kontestasi Islam di Indonesia: Antara Menjaga Tradisi dan Otoritas, Jakarta: LP3ES, 2022.
Steenbrink, Karel, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
Syarif, Fajar dan Muhammad Ansor, “Mosque and Reproduction of Arab Identity in The Hadrami Community in Betawi”, Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage Vol. 9. No. 1 pp. 78-114.
Artikel di atas merupakan karya dari Gifari Juniatama, peserta lomba artikel dalam rangka Harlah 1 Tahun NU Online.
Terkini
Lihat Semua